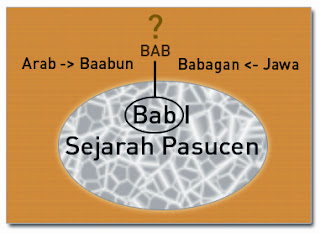Tintin masih di Bandung. Kali ini, bukan misi petualangannya. Bukan juga investigasi prostitusi, bukan pula wisata kuliner.
Tetapi, dihadirkan langsung oleh Sang Petualang Data, Anton Kurnia, sebagai objek kajian eksplorasi dan perbandingannya. Mulai dari zaman kelahiran hingga zaman plesetan. Termasuk, juga iklan hingga relasi kenegaraan.
Semuanya ditulis dan dirangkum dibawah empat judul tulisan dalam lembar Telisik halaman ke-21 hingga ke-22 di koran Pikiran Rakyat. Pada Edisi Senin (Wage) 1 Desember 2014 ini lah empat judul tulisan Anton Kurnia itu diberi aran : Tintin : Kisah Seru Wartawan Petualang; Herge, Sang Komikus Legendaris; Petualangan Tintin di Indonesia; dan Tintin Imitasi, Komik Parodi, dan Jokowi.
Usai menyimak "Tintin Imitasi, Komik Parodi, dan Jokowi," ragam adegan imajinasi ini kembali menguntit. Usai kubuka pintu intipan, aku menemukan beragam ingatan yang memantik senyum hingga gregetan.
Oh ya, sebelum dalam Iklan Kampanye Politik Indonesia, Tintin sempat muncul pada poster-poster iklan Wisata Indonesia. Saya lupa agen iklan mana yang mengadopsi Tintin dalam gambar hitam-putih itu. Yang jelas, tokoh Protagonis dalam dongeng lesan maupun cerita terekam juga tertulis, cukup seksi untuk dijadikan objek kepentingan di luar bingkai global suatu kisah. Tetapi, menurut saya, tindakan melesatkan atau mutilasi karakter semacam itu rentan mengancam karakter asli suatu karya. Jika tragedi semacam itu menimpa konsumen awam dan lugu, maka suatu karya, tokoh, dan Peng-karya-nya, bisa-bisa bakal terciprat getahnya.
Memang, tidak ada salahnya seorang pengagum dan penyuka idolanya meniru dan mencuri hal-hal positif dari Sang Idola. Namun, jika tindakan itu diplesetkan hingga mengancam pihak lain atau -bahkan- idolanya sendiri, saya kira, perlu adanya rekayasa pertimbangan ulang.
Ini bukan cuma soal plesetan yang mengarah pada pornografi, pornoaksi, relasi politis, politik praktis, hingga ajakan-ajakan (dakwah) lain yang dikemas dalam beragam kesan dan pesan. Tapi juga, soal keberlangsungan pengidola lain dalam proses memutar ulang kenangan, menghayati, menjaga, hingga menjustifikasi Sang Idola di kemudian hari.
Jika tindakan pemplesetan -atau penafsiran ulang- itu kebetulan cocok dengan apa yang diminati orang-orang awam, sangat mungkin tidak akan langsung menimbulkan masalah. Namun, dari kalangan awam maupun fasih yang tidak cocok dengan latar belakang, proses, hingga hasil yang muncul usai terjadinya tindakan itu, sangat mungkin akan melawan.
Cukup maklum jika perlawanannya itu dialamatkan pada tindakan pemplesetan. Namun sangat disesalkan jika ketidakmampuan melawan tindakan pemplesetan itu malah balik melawan, membenci, dan menghujat hal-hal yang diplesetkan pihak-pihak yang ditentang. Yang dalam hal ini, bisa mengarah suatu karya, idola, penulis, hingga orang lain yang tidak tahu menahu permasalahan itu namun sama-sama mengidolakan suatu karya yang sama.
Sebatas konteks itulah, saya sempat risih saat ada iklan televisi lokal yang melibatkan imaji publik dan tokoh punakawan dalam gelaran wayang juga ketoprak. Dalam iklan yang konon sebagai Iklan Masyarakat itu, ada beberapa punakawan yang sedang ngasap tembakau di sebuah warung. Akhir dari iklan pemerintah lokal itu tadi, mengajak warganya untuk menjadikan desa mereka sebagai “Desa Bebas Asap Rokok”.
Tentu bukan soal kontroversi regulasi, politik dibalik hukum, dalih kesehatan, dalih ekonomi, dalih etika, dan dalih budaya. Yang saya sayangkan, kenapa konsep iklan itu melibatkan tokoh-tokoh yang sudah merasuki imajinasi bawah-sadar publik untuk dibenturkan pada publik itu sendiri. Padahal, ujung goal pada iklan itu sendiri masih berbuntut kontroversi yang rumit.
Selain punakawan, tentu masih banyak tokoh-tokoh protagonis dalam suatu cerita atau karya yang dilihkan perannya secara paksa, kentara, maupun samar-samar. Entah dalam produk komersil maupun nir-laba, semacam organisasi dan komunitas tertentu.
Walau begitu, sekali lagi, tidak ada salahnya jika para pengidola atau penyuka seorang tokoh itu ingin menjadi (wanna be) atau meniru-niru hal-hal yang dianggap patut ditiru dari Sang Tokoh. Tetapi, jika tindakan meniru Sang Tokoh itu diwujudkan secara verbal dan dibenturkan pada mereka-mereka yang suka namun awam dalam beragam kepentingan dan pertimbangan, maka rentan terjadinya bencana “kesurupan massal”.
Jika menjelma efek “positif”, tanpa kontroversi, dan berkepanjangan, maka teori kesurupan selama ini tidak selamanya jelek. Namun, jika pada masa-masa ketidaksadaran itu ternyata banyak “efek samping”-nya bagi publik, maka dapat dipastikan, bahwa itulah tanda-tanda kesuksesan pihak-pihak berkepentingan di belakang marketing dan sales.
Memang, rentannya potensi permasalahan semacam itu, bisa dikembalikan lagi pada diri kita sendiri-sendiri. Serumit, sejauh, dan separah apapun gelagat negatif pihak-pihak yang memanfaatkan “tokoh suci” dalam imajinasi, akan redup dengan sendirinya jika kita mampu mengidentifikasinya. Tindakan memelintir kenangan dan ajaran yang dilakukan di atas kepentingan-kepentingan kusam, bakal balik dengan sendirinya. Tentunya, perlu adanya tindakan lanjutan sebagai bentuk penangkalan.
Setidaknya, dengan menyimak karya-karya eksplorasi, perbandingan, dan analisa kepentingan, kita bisa meningkatkan wawasan dan jeli dalam mengidentifikasi keaslian karakter suatu tokoh. Dan, terkait tokoh Tintin, tidak ada dari Herge yang mengajak pembaca untuk turut serta ”berwisata wanita”.
Jika menemukan karya-karya yang melibatkan Tintin dan tokoh-tokoh positif lainnya dalam durasi pornografi, pornoaksi, iklan produk, dan semacamnya, itu kemungkinannya datang dari pihak ketiga. Akan lebih bagus jika karya-karya semacam itu disingkirkan terlebih dahulu sebelum anak-anak atau adik-adik kita mampu menganalis kepentingan di balik itu semua. Termasuk, juga efek-efeknya. []